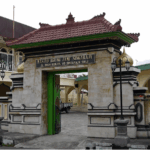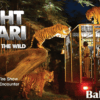Hi sobat Balipedia.ID
Barusan mimin ketemu artikel menarik di Fb yang sumbernya berasal dari Majalah Raditya, Majalah Hindu Pertama dan terbesar di Indonesia. Mimin sering mendengar kabar kalau sebagian masyarakat Bali (beragama Hindu) bisa jatuh miskin karena faktor upacara Agama. Benarkah demikian? Mari kita simak tulisan Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda berikut ini…
Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, dahulu bernama Putu Setia – Jurnalis TEMPO Media Grup. Sejak menjadi pendeta Hindu, 21 Agustus 2009, tinggal di Pasraman Dharmasastra Manikgeni, Desa Pujungan, Kabupaten Tabanan, Bali.
Oleh Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda
 PEMDA Provinsi Bali akhirnya menyelenggarakan dialog soal kemiskinan yang dipengaruhi unsur upacara agama. Sebelumnya secara berturut-turut koran ini memberitakan masalah itu. Kemiskinan itu sendiri adalah fakta karena berdasarkan pendataan Biro Pusat Statistik. Kaitannya dengan upacara keagamaan juga fakta, karena menjadi pengeluaran kedua di sektor nonmakanan. Adapun yang salah adalah kemiskinan itu bukan disebabkan oleh ajaran agama, tetapi salah dalam menerapkan ajaran agama. Jadi yang pegang dominan adalah adat istiadat setempat yang melahirkan budaya agama yang boros.
PEMDA Provinsi Bali akhirnya menyelenggarakan dialog soal kemiskinan yang dipengaruhi unsur upacara agama. Sebelumnya secara berturut-turut koran ini memberitakan masalah itu. Kemiskinan itu sendiri adalah fakta karena berdasarkan pendataan Biro Pusat Statistik. Kaitannya dengan upacara keagamaan juga fakta, karena menjadi pengeluaran kedua di sektor nonmakanan. Adapun yang salah adalah kemiskinan itu bukan disebabkan oleh ajaran agama, tetapi salah dalam menerapkan ajaran agama. Jadi yang pegang dominan adalah adat istiadat setempat yang melahirkan budaya agama yang boros.
Ritual dalam ajaran agama apapun tak pernah membebankan umat. Dasar dari yadnya adalah tulus ikhlas dan bhakti yang oleh umat Hindu disebut lascarya. Yadnya yang dilakukan tanpa ketulus-ikhlasan tergolong yadnya rajasik, ada pamrih untuk jor-joran. Hura-huranya lebih banyak dibandingkan rasa bhaktinya. Lalu kebiasaan setempat yang diwariskan di masa lalu tak berani untuk dibuang meski zaman sudah berubah. Banyak sekali contoh yang bisa disebutkan.
Misalnya, upacara ngaben (pitra yadnya). Dalam sastra Hindu disebutkan, layon dalam perjalanan menuju kuburan untuk dibakar atau dipendem (ditanam) paling utama jika diusung oleh sanak keluarganya (pratisentana). Tetapi budaya yang diwariskan, layon itu dibuatkan wadah (bade) yang indah padahal hanya untuk dibakar. Maka muncullah biaya membuat bade. Akibatnya merembet, karena ada bade sebagai sarana mengusung jenazah maka perlu dipelaspas. Maka muncullah biaya banten pemelaspas. Bade itu ada kalanya besar karena bertingkat yang disesuaikan dengan tingkatan meru di pura kawitan. Maka banten pemelaspas pun makin besar. Di kalangan tertentu bade itu ada pula berisi naga banda, maka runtutannya ada banten untuk “menghidupkan naga banda” kemudian ada banten untuk “memanah naga banda”. Karena bade besar perlu minta bantuan banyak orang untuk mengusungnya, maka runtutannya perlu pengusung diberi “hadiah”, misalnya, baju kaos seragam. Perlu pula bantuan pecalang untuk mengamankan perjalanan bade ke kuburan, termasuk memotong kabel listrik yang menghalangi di jalan. Jadi semakin banyak perlu orang dan semakin banyak perlu biaya. Ini persoalan adat dan budaya, bukan persoalan ajaran agama.
Kalau keluarga itu kaya tidak masalah. Tetapi bagaimana kalau keluarga itu tak punya, akhirnya menjual tanah warisan dengan dalih untuk upacara ngaben orang tuanya. Kalau warisan sudah dijual, sudah tentu keluarga itu akan semakin tidak punya. Maka pantaslah jadi miskin.
Apakah pemuka agama dan sulinggih tak mau memberikan pencerahan yang mana ajaran agama dan yang mana adat budaya? Sudah banyak dilakukan tetapi kesadaran mayarakat untuk menerima penyederhanaan ini tidak sepenuhnya mudah. Mereka masih melihat ke masa lalu dan sulit untuk meninggalkan tradisi “nak mula keto”. Tahun lalu ada keluarga dadia saya mau melaksanakan ngaben dengan “tanpa bade”, layon cukup dibawa ke kuburan dengan pengusung yang dihias seadanya. Banten pun kecil sejak nyiramang, ngaskara sampai di setra. Hanya habis Rp 3,5 juta. Biayanya sama dengan ikut ngaben massal, namun saat itu ngaben masal baru saja lewat sebulan lalu.
Yadnya massal (lebih tepat disebut yadnya bersama) sudah populer saat ini dan membantu mengatasi masalah biaya. Untuk metatah (potong gigi) bersama biayanya tak sampai Rp 300.000. Bahkan banyak pasraman atau peguyuban yang membebaskan biaya bagi mereka yang tidak mampu. Namun ego untuk jor-joran dan berhura-hura justru tetap terjadi. Yang potong gigi pergi ke salon dan menyewa pakaian gemerlapan bak raja dan ratu, sampai habis Rp 900.000. Jadilah ritual dengan unsur pamer, foto-foto, kemudian diunggah ke Face Book. Mending kalau ada uang. Kalau sampai menjual harta warisan atau telat membayar SPP dan berhenti sekolah, maka ritual agama jadi kambing hitam untuk disalahkan.
Selain pencerahan pemuka agama dan sulinggih, yang sesungguhnya diperlukan saat ini adakah gerakan moral atau revolusi mental orang Bali dalam menghadapi ritual agama. Juga sifat konsumtif. Jangan agama yang disalahkan ketika orang jadi miskin, salahkan prilaku mereka dalam melaksanakan ritual itu. (*)
Sumber: Majalah Raditya